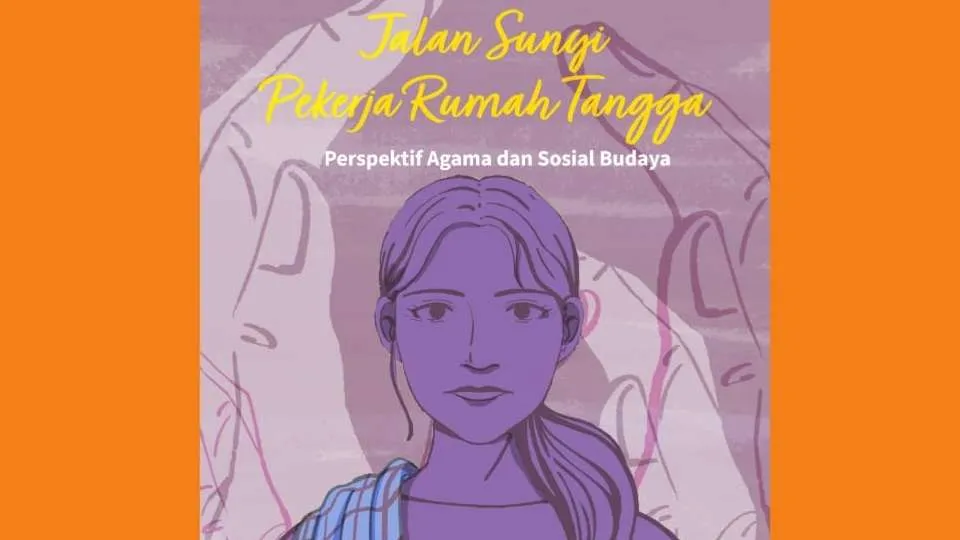
Rahim Perempuan Diperalat Sebagai Penerus Perbudakan Tradisional di Sumba
Oleh Martha Hebi (Judul asli tulisan ini Rahim Perempuan Diperalat Sebagai Penerus Perbudakan Tradisional yang bersumber dari buku Jalan Sunyi Pekerja Rumah Tangga Perspektif Agama dan Sosial Budaya oleh Komnas Perempuan pada 2022)
Rahim Perempuan Diperalat Sebagai Penerus Perbudakan Tradisional
“Itu Y, dia baru dibelis dua minggu yang lalu. Dia dari Desa U. Dia tinggal dengan Umbu nai Z sekarang,” [2]seorang perempuan 40an tahun menunjukkan kepada saya seorang perempuan remaja belasan tahun yang lewat di depan rumahnya. Keesokan harinya, anak perempuan tadi berpapasan dengan saya. Dia tersenyum malu-malu. Kami berkenalan.
Y berusia 12 tahun. Dia “dijual” kakeknya ke keluarga bangsawan, Umbu nai Z. Kakek Y mendapatkan sejumlah ternak sebagai ganti dari penyerahan Y ke bangsawan ini. Seterusnya Y akan menjadi hamba untuk keluarga ini. Y tidak tahu bahwa akan menjadi korban “jual-beli” orang.
Percakapan kami ini terjadi pada tahun 2003 di sebuah desa di Kabupaten Sumba Timur, saat saya terlibat sebagai anggota peneliti lokal dalam penelitian sosial. Kisah seperti ini bukanlah peninggalan masa lalu yang jadi catatan sejarah perbudakan Sumba. Perbudakan masih hidup dan bertumbuh di Sumba! Dia ibarat darah yang mengalir dalam tubuh. Kita tidak melihatnya –kecuali terluka—tapi kita tahu dia ada di dalam tubuh.
Menelusuri Jejak Perbudakan di Sumba
Sumba Timur adalah satu dari empat kabupaten di Pulau Sumba, yang terletak di paling timur pulau ini. Lainnya Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Sumba Timur merupakan kabupaten terluas di Pulau Sumba, bahkan jika ketiga kabupaten lainnya digabungkan. Luas Sumba Timur 7,000 km2 dari total luas Pulau Sumba 10,710 km2.
Praktik perbudakan dan perdagangan budak ada di Pulau Sumba dan Nusa Tenggara secara umum. Mengutip I Ketut Ardhana (2005) “Selain kayu Cendana, Nusa Tenggara juga terkenal dengan perdagangan budaknya. Sebagai contoh, sejak abad ke-16 (1516), selain Cendana, kayu madu dan lilin, budak juga dapat diperoleh dari Pulau Sumba. Kebanyakan di antara mereka adalah anak berusia 8-14 tahun.”[3]
Pater Robert Ramone, CSsR, Direktur Lembaga Studi dan Pelestarian Budaya Sumba, Tambolaka Sumba Barat Daya, mengungkapkan hal senada terkait sistem perdagangan dunia dan perbudakan pada abad ke-15.
“Sumba tidak menjadi tempat tujuan Portugis dalam misi perdagangannya. Tujuan mereka bukan di sini. Hanya tempat transit karena Sumba sangat favorit untuk Eropa. Ada tiga hal yang mereka cari dan ada di Sumba, pertama kayu cendana, Sumba dulu terkenal dengan sebutan Pulau Cendana, kedua itu kuda dan ketiga itu budak belian. Saya pernah berkunjung ke Gowa, Sulawesi Selatan, lebih tepatnya saya ke museum, dekat paroki teman saya. Saya lihat di sana [museum], Gowa itu Kesultanan Islam yang terkenal, itu jalur utara. Nah jalur selatan ada Kesultanan Bima. Kesultanan Bima dan Gowa ini sangat terkenal karena perdagangan budak, merekalah yang mensuplai apa yang dibutuhkan Portugis, cendana, kuda dan budak. Kemudian menyebar ke pulau-pulau sekitarnya seperti Flores, Sumba dan Timor ya untuk mencari bahan yang dibutuhkan tadi.”[4]
Pater Robert mengisahkan lokasi tempat lembaganya saat ini, yang juga dikenal dengan nama Rumah Budaya, adalah lokasi penampungan budak pada abad ke-15. Kalembu Nga’a Bangga nama tempatnya. Dalam bahasa Loura (Sumba Barat Daya) berarti lembah atau semak belukar tempat memberi makan anjing.
“Nama tempat ini berarti semak belukar tempat memberi makan anjing. Tapi anjing yang dimaksud adalah budak belian yang diidentikkan dengan anjing. Ini masalah penghargaan martabat manusia, mereka disejajarkan dengan anjing. Sebelum budak belian ini diberangkatkan ke Pelabuhan Waikelo mereka diberi makan dulu, ini tempat penampungan, ya di sini. Entah diberi makan atau tidak, tapi tempat penampungan ini ada tanda atau bukti, antara lain kalele. Dalam Bahasa Loura, kalele itu artinya lingkaran batu. Dalam kalele ini tempat penampungan manusia, budak belian tadi. Saya juga awalnya tidak tahu bahwa tempat ini bersejarah, tetapi saat pendirian lembaga kami, tua-tua adat yang beritahu saya. Ya tepatlah dibangun lembaga kami ini yang salah satu tugasnya menhormati harkat dan martbat manusia sebagai gambar dan citra Allah. ”[5] Kalembu Nga’a Bangga berjarak sekitar 6 km dari Pelabuhan Waikelo di Sumba Barat Daya. Menurutnya budak yang ditampung di Kalembu Nga’a Bangga ini didominasi oleh Suku Loura, Wejewa/Wewewa dan Kodi, semuanya berada di Sumba bagian barat daya. Pada abad ke-15 masih sangat sulit transportasi dari Sumba bagian timur ke Sumba bagian barat daya.
Budak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti hamba; jongos; orang gajian. Budak belian berarti orang yang dibeli dan dijadikan budak. Perbudakan adalah suatu perbuatan atau keadaan yang membuat seseorang menjadi budak, yang merupakan objek properti yang dimiliki oleh orang lainnya. Perbudakan biasanya terjadi dengan orang yang diperbudak dibuat untuk melakukan beberapa bentuk pekerjaan dan lokasi mereka juga ditentukan oleh orang yang memilikinya.[6]
Istilah budak dalam bahasa Inggris disebut dengan slave yang berasal dari kata slav. Menurut Enclyclopedia Britanica,kata slav merujuk pada bangsa Slavia yang ditangkap dan dijadikan budak saat perang awal abad pertengahan (abad ke-5 hingga abad ke-15 Masehi).[7]
Secara umum ada tiga kasta dalam stratifikasi sosial di Sumba Timur. Pertama maramba atau kaum bangsawan, kedua kabihu[8] atau kaum merdeka dan ketiga ata/tau la umma[9] atau kaum hamba. Oe. H. Kapita dalam F.D. Wellem (2004) menuliskan bahwa awalnya masyarakat Sumba dibagi menjadi empat golongan yaitu ratu (imam), maramba, kabihu dan ata. Dalam perkembangan kemudian golongan ratu dipersatukan dengan golongan maramba sehingga menjadi tiga golongan saja.[10]
Ratu (Rato di Sumba Barat dan Sumba Barat Daya) adalah imam Marapu. Ratulah yang bertugas memimpin hamayang (sembayang/ibadah) umat Marapu. Marapu adalah agama asli orang Sumba. Jika ditelusuri, Marapu sudah ada di Sumba lebih dari 2500 tahun. Marapu adalah salah satu agama asli di Indonesia yang mengalami diskriminasi oleh negara.[11].
Stratifikasi sosial ini secara turun temurun terwariskan ke ketiga strata ini. Yang bangsawan telaplah seterusnya bangsawan demikian juga dua strata lainnya. Saya menamainya ‘genetika sosial’. Yang saya ketahui ada satu hal (bisa jadi bukan satu-satunya) yang dapat menimbulkan ‘mutasi genetika sosial’ yaitu perkawinan. Jika seorang laki-laki bangsawan menikah dengan perempuan hamba, maka ‘derajat’ kebangsawanannya akan berkurang, meskipun dia tetaplah seorang bangsawan. Akan tetapi jika perempuan bangsawan menikah dengan laki-laki hamba maka strata perempuan ini mengikuti suaminya. Jika seorang perempuan hamba menikah dengan laki-laki bangsawan maka strata perempuan akan mengikuti suaminya. Di sini potret feodalisme di Sumba berbarengan dengan spirit patriarkhi yang sangat kuat.
Tiga Golongan Hamba
Dalam masyarakat Sumba Timur dikenal tiga golongan hamba atau budak dengan pengertian dan tugasnya masing-masing: ata ndai, ata ngandi dan ata pakei.[12] Pertama, ata ndai. Mereka adalah hamba yang dimiliki oleh keluarga para maramba (bangsawan) secara turun-temurun. Biasanya nama si hamba dikaitkan dengan nama tuan yang memilikinya (secara pribadi). Misalnya, bangsawan laki-laki bernama Umbu nai Luta. Artinya, dia memiliki hamba bernama Luta. “Umbu nai” bermakna umbu-nya atau tuan-nya. Jika dia seorang perempuan, misalnya Rambu nai Lemba, berarti perempuan ini adalah bangsawan yang memiliki hamba bernama Lemba. Karena bersifat turun-temurun, maka para hamba akan mengabdi pada sebuah keluarga secara turun-temurun pula. Tak heran kalau ada keluarga bangsawan yang setiap anaknya memakai nama dari hamba (pribadi) masing-masing.
Kedua, ata ngandi, adalah hamba yang dibawa oleh perempuan bangsawan saat menikah dan pindah rumah. Hamba ini akan selalu bersama tuannya, laksana asisten pribadi yang dapat dimintai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Namanya bisa juga melekat pada nama tuannya. Sedangkan golongan ketiga adalah ata pa’kei. Mereka golongan hamba yang dibelis[13] atau “dibeli” dengan membayar mahar (dalam bahasa Kambera: pa’kei= yang dibeli). Belis terhadap hamba dilakukan oleh bangsawan atau golongan biasa (bukan bangsawan) yang secara mapan secara ekonomi dengan cara memberikan sejumlah ternak kepada keluarga yang mau menyerahkan kerabat atau anak perempuannya sebagai hamba. Kelak, hamba perempuan atau anak perempuan mereka akan dinikahkan dengan hamba laki-laki di dalam keluarga yang memberi belis tadi.
Belis biasanya bermakna mahar, serahan dalam adat perkawinan masyarakat Sumba. Keluarga pihak laki-laki melamar keluarga perempuan dengan hantaran serupa ternak: kerbau atau kuda. Sebaliknya keluarga perempuan akan membalasnya dengan kain sarung tenunan yang indah dan benilai tinggi.
Y dalam kisah di atas masuk dalam golongan ata pa’kei. Belis yang terjadi pada Y, bukanlah bagian dari adat perkawinan. Ini adalah tradisi lain yang dinamai belis hamba. Belis hamba tidak terlalu popular lagi saat ini. Namun diam-diam tetap juga terjadi di desa maupun di kota. Ya, ibarat darah tadi, kita tahu ada tapi tidak terlihat-seolah-olah tidak melihatnya. Perempuan dewasa atau anak perempuanlah yang menjadi obyek tradisi ini.
Tugas Para Hamba
Apa saja tugas para hamba? Seperti dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sumba, ada pembagian kerja antara hamba dewasa, laki-laki dan perempuan. Perempuan hamba mengerjakan “pekerjaan perempuan” seperti memasak, membersihkan rumah, menjaga anak, mengambil kayu mati untuk memasak, timba air, cuci pakaian, beri makan babi, ayam, ada juga yang membantu di ladang atau sawah.
Penuturan Yuli (18 tahun):
“…. saya ikut bos perempuan waktu umur 5 tahun atau mungkin 4 tahun. Dia pindah di sini ikut bos laki-laki waktu dorang [mereka] nikah. Waktu saya masih kecil, saya jaga anaknya bos. Dorang suruh juga ambil kayu api, timba air. Waktu sudah mulai besar, lebih banyak kerja lagi….. timba air untuk masak makannya kita, untuk makan babi, untuk kasih minum kuda, cuci pakaian, masak, kasih bersih rumah, buat kopi teh untuk bos laki-laki, bos perempuan, kasih makan babi, urus kebun…… Sampai hamil besar juga saya tetap kerja itu, sampai mau melahirkan. ”[14]
Penuturan Danga (24 tahun):
“..dorang mau suruh saya jadi ngara hunga[15] anak pertamanya bos, saya tidak mau. Tapi tidak bisa omong. Saya mau keluar dari rumahnya bos, pergi cari kerja di tempat lain……. Kerja dari jam berapa e, dari pagi sudah. Bangun jam 5. Masak, timba air di mata air, bersihkan rumah, cuci piring, cuci pakaian, cari kayu api, jaga anaknya bos. Memang kita tidur siang juga. Tapi tidak boleh pergi-pergi, apalagi kalau mau merantau.”[16]
Laki-laki hamba seperti laki-laki Sumba pada umumnya bekerja di kebun atau sawah, cari rumput kuda, rawat kuda, ada juga yang membantu pekerjaan perempuan hamba, atau pekerjaan lain yang diperintahkan oleh tuan mereka.
Penuturan Huki (40 tahun)
“…..saya sekarang tidak tinggal dengan bos lagi. Dorang (mereka) sudah buat rumah baru jadi kami sudah yang tinggal di sini. ……kalau ada pekerjaan yang butuh saya, baru bos panggil. Kita kerja bantu dorang sudah. Kalau masih tinggal sama-sama, kita kerja semua hal sudah, Ibu. Perkerjaan laki-laki sudah. Pergi kebun, urus hewan, kasih minum hewan.”[17]
Ada juga tugas hamba anak-anak, laki dan perempuan. Biasanya membantu orang tua mereka, anak perempuan membantu ibunya, laki-laki membantu ayahnya. Ada hamba yang sejak kecil sudah “dinobatkan” menjadi hamba tuan kecilnya (ngara hunga), maka dia mesti mendampingi tuan kecilnya bermain, ke sekolah, ke mana pun si tuan kecil pergi.
Penuturan Retang (anak laki-laki, 10 tahun), hamba dari Umbu Hapu (12 tahun) kelak Umbu Hapu akan dipanggil Umbu nai Retang (tuangnya Retang):
“…….. saya sama-sama dengan Umbu [sapaan untuk laki-laki dalam Bahasa Kambera] pergi sekolah, pegang tasnya Umbu, kalo Umbu suruh tulis waktu di sekolah, saya tulis sudah……Kita main kartu sama-sama, main karet juga….saya pigi kasih minum kuda, ambil rumput kuda, kalau tidak ada kayu api, saya pigi cari.”[18]
Hasil pengamatan: Kahi (15 tahun) mendapat tugas menjaga anak tuannya yang berusia 6 bulan. Selain menjaga anak, Kahi juga harus mengerjakan pekerjaan rumah lainnya, misalnya timba air, masak, cuci piring. Ami (13 tahun) bertugas tumbuk padi, timba air dan siram tanaman.[19]
Penyebutan ata atau hamba mengalami perubahan. Tidak diketahui pasti kapan istilah tau la umma mulai dipakai untuk menyebut ata. Sekitar awal tahun 2000an sering terdengar penyebutan ata sebagai saudara di (dalam) rumah. Pada tahun 2020/2021, pertama kali mendengar dengan sebutan kawan dalam rumah atau kawan rumah. Meskipun penyebutannya berubah, namun statusnya tetaplah hamba.
Unpaid Labour-Kerja Gratis, Ibu!
Peran para hamba yang bekerja untuk para bangsawan ini, tidak mendapatkan gaji seperti pekerja rumah tangga atau pekerja di toko, perusahaan.
Penuturan Huki (40 tahun)
“….Aii tidak bayar lagi, Ibu. Kita khan tau la umma…. …..untung bos baik, Ibu. Saya kerja kebun sama-sama dengan bos, tanah milik orang tuanya bos….memang kita bantu sudah untuk urus kebunnya bos juga. Hampir 3 atau 4 hektar.”[20]
Yuli (18 tahun)
“…. Aii tidak ada gaji, Ibu. Begitu sudah kalau tau la umma. Kita sudah yang kerja semua.”[21]
Danga (24 tahun)
“……mo bayar apa lagi, Ibu, tidak bayar sudah, Ibu. Kerja gratis, Ibu. Malahan kalau kita dapat uang waktu pergi kerja kumpul batu, kita beli beras untuk makan semua”[22]
Meskipun tidak dibayar, namun ada hamba yang mendapatkan lahan. Ada yang diserahkan dan dapat menjadi hak milik, ada juga yang hanya mendapatkan hak guna pakai. Laki-laki hamba juga mendapatkan bagi hasil dari ternak yang mereka rawat. Misalnya kerbau, sapi dan kuda. Sedangkan perempuan hamba mendapatkan bagi hasil dari ternak babi atau kambing milik bangsawan yang mereka rawat. Umumnya mereka juga memelihara ayam dan bisa dijual.
Hamba yang tinggal di rumah lain dengan para bangsawan sedikit lebih beruntung karena tidak sepenuhnya bekerja untuk urusan rumah tangga bangsawan. Sedangkan hamba yang tinggal bersama bangsawan memiliki rutinitas kerja harian dalam rumah tangga bangsawan yang memilikinya.
Rahim yang Dikuasai!
Rahim perempuan kerap dimetaforakan sebagai rumah kehidupan sehingga dunia ini memiliki sejarah, sebagai penerus peradaban. Dalam budaya Sumba (4 kabupaten), mamuli atau mamoli berbentuk menyerupai rahim perempuan merupakan simbol kesuburan dan perempuan itu sendiri. Belum diketahui persis abad ke berapa mamuli hadir dalam budaya Sumba.
Sejak tahun 2003, dari hasil pengamatan dan wawancara yang saya lakukan, menunjukkan ada fenomena penguasaan terhadap perempuan hamba atau perempuan yang kurang punya kekuatan jaringan keluarga atau jaringan sosial. Pola penguasaan berindikasi bahwa mereka dipakai untuk melahirkan anak dan memperbanyak keturunan. Berikut beberapa hasil wawancara dan pengamatan saya.
Perempuan hamba yang kandungannya gugur dua kali berturut-turut.
Ngguna, sekitar 22 tahun, seorang perempuan hamba yang tinggal bersama sebuah keluarga bangsawan dengan 4 orang perempuan hamba lainnya. Dia memiliki seorang anak perempuan, Yeni, berusia 5 tahun. Sehari-hari Ngguna bertugas mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Pagi hari, masak air untuk buat teh, kopi dan persediaan air minum. Dilanjutkan masak nasi untuk pagi. Setelah memasak Ngguna, akan tumbuk padi untuk makan siang nanti atau untuk makan malam untuk seluruh penghuni rumah. Di dalam rumah ada tuan besar dan nyonya, tuan muda (anak pertama) dan istri serta empat orang anak mereka, tiga perempuan hamba dengan suami mereka dan anak-anak mereka, seorang perempuan hamba balasan tahun, Ngguna dan suaminya serta Yeni. Ada 20an orang.
Jika pakaian kotor banyak, maka di pagi hari setelah masak untuk sarapan, Ngguna mencuci perlatan makan dan menanak nasi untuk siang, dia akan melanjutkan mencuci pakaian di sungai kecil dekat tempat tinggalnya.
Setelah makan siang biasanya Ngguna mencuci peralatan makan, istrahat sebentar dan dilanjutkan dengan persiapan makan malam, seperti tumbuk padi, petik sayur di kebun. Petik sayur di kebun dilakukan sekaligus dengan menyiram sayuran di kebun. Ngguna menimba air dengan ember hitam berisi 12 liter atau 20 liter, tergantung ember yang ada saat itu. Luas kebun yang ditanami sayur sekitar 3 are. Dia dibantu Yeni, anaknya perempuannya. Yeni mengangkat air di ember kecil berkuran 5 liter.
Rutinitas lainnya, mempersiapkan dan memberi makan babi pagi dan sore, mencari kayu mati untuk masak. Pekerjaan-pekerjaan ini dibantu juga oleh perempuan hamba lainnya. Perempuan hamba lainnya ada yang memiliki tugas utama menjaga dan mengurusi keperluan cucu-cucu tuan besar dan nyonya yang tinggal bersama mereka. Ada yang bertugas untuk kebersihan dan kerapian rumah.
Ngguna bukanlah ngara hunga dari nyonya besar jadi dia tidak perlu selalu berada di sekitar nyonya. Biasanya hamba yang menjadi ngara hunga tuan atau nyonya akan selalu berada tidak jauh dari tuan atau nyonya. Karena mereka yang akan selalu membantu tuan atau nyonya untuk hal-hal personal, misalnya perempuan hamba yang menjadi ngara hunga, menata pakaian, membuatkan kopi atau teh, mempersiapkan makanan. Mereka juga tahu lokasi penyimpanan barang-barang pribadi nyonyanya.
Ngguna sudah dua kali keguguran saat usia kandungannya sekitar tiga bulan. Keguguran ini dalam waktu yang berdekatan. Tidak sampai enam bulan.
“Saya keguguran dua kali. Tiba-tiba darah keluar waktu saya hamil. Pertama sedikit saja, baru jadi banyak. Saya sementara kerja. Jadi Rambu [nyonya besar] suruh saya istrahat. Saya rasa sakit sekali di sini [Ngguna menunjuk bagian bawah perut]. Istrahat lama juga mungkin satu minggu atau dua minggu. Saya tidak kerja, hanya bantu masak air dan masak nasi saja. Tidak kerja lain.Tidak lama lagi saya hamil, tapi keguguran lagi. Saya tidak tahu juga kenapa,” cerita Ngguna. [23]
Kisah lain dituturkan perempuan bukan hamba.
Diana berusia 21 tahun saat dia menuturkan kisahnya dengan lengkap. Kami sudah bertemu, sekitar enam kali, sebelum dia menuturkan kisahnya ini. Diana adalah perempuan dengan kasta kabihu. Orang Dia sedang menempuh pendidikannya di bangku SMP pada tahun 2015. Saat itu dia berusia 16 tahun, sedang mempersiapkan diri untuk ujian akhir SMP. Sejak duduk di bangku SMP, Diana tinggal di rumah gurunya yang lebih dekat dengan sekolah. Tinggal di rumah guru di sekitar sekolah biasa terjadi di pedesaan Sumba untuk membantu siswa yang rumahnya jauh dari sekolah agar lebih fokus belajar dan bisa didampingi guru tempat tinggalnya untuk belajar.
Baru dua atau tiga bulan tinggal bersama guru, Diana sakit dan harus berobat ke Waingapu. Setelah membaik, Diana tidak pulang ke rumah guru tetapi ke rumah orang tuanya. Diana berencana kembali ke rumah guru untuk meneruskan sekolahnya karena waktu ujian sudah makin dekat. Menjelang dia kembali ke rumah gurunya, Hapu, berusia 50an tahun seorang laki-laki maramba, yang di desanya datang ke rumahnya.
“Waktu itu hanya saya dengan mama yang ada di rumah. Dia [Hapu] tanya sama saya, kau anaknya siapa. Jadi saya jawab saya anaknya saya punya bapa dan mama di sini. Dia sering datang lagi, saya tidak ingat jarak berapa hari. Beberapa minggu kemudian, dia datang dengan istrinya. Mereka datang bersama orang dalam rumah [hamba]. Mereka bawa satu ekor kambing, sikat gigi, sabun, odol. Dia punya istri bilang, saya nanti bantu siap air mandi dan makan untuk dia [Hapu]. Tiga hari kemudian, dia datang jemput saya, dia bilang apparat desa ada perlu. Jadi saya ikut. Tapi kami malah ke kiosnya. Malam harinya di kios ini dia perkosa saya. Dua kali. Waktu itu juga saya rasa saya sudah mati.”
Sejak saat itu Diana tidak pulang lagi ke rumahnya. Dia tinggal di rumah Hapu, di sana dia diberitahu bahwa dia telah menjadi istri kelima Hapu. Di rumah itu, Diana harus bekerja keras dengan hamba-hamba lainnya. Bersama hamba lainnya,Diana tidur jam 11 malam, nanti subuh jam 3 atau jam 4 sudah bangun. Hampir setiap hari DIana mendapat caci maki dari istri Hapu. Pekerjaan DIana, cari batang pisang di kebun, memikulnya ke rumah, diris untuk makanan babi pagi dan sore. Selain itu Diana bekerja dengan hamba lainnya antara lain cuci pakaian, masak, membersihkan rumah, siapkan makan untuk suaminya, mengambil kayu mati untuk masak.
“Dia bilang sapa suruh kau datang tidak bawa hamba. Jadi sekarang kau kerja sudah too.” Diana pernah berusaha lari ke rumah orang tuannya, namun langsung dijemput lagi untuk kembali dan tinggal di rumah Hapu. Orang tuanya tidak berdaya. “Mereka orang kuat di desa. Semua orang ikut dorang punya mau sudah. Kita takut juga.”
Beberapa bulan kemudian Diana hamil. Dalam keadaan hamil, Diana tetap bekerja. Pekerjaannya lebih ringan dari sebelumnya. Beberapa bulan setelah anaknya lahir, Diana kembali bekerja seperti biasa. Anaknya diasuh oleh istri-istri Hapu lainnya. Dan amarah serta caci maki istri Hapu [yang ikut menjemput Diana] terus berlanjut. Hapu juga pernah menjambak rambutnya dan menendangnya. Bahkan pernah mengancam Diana dengan parang di leher Diana.
“Saya hampir bunuh diri. Saya mau gantung diri. Tapi saya ingat saya punya anak, saya ingat ada keluarga saya jadi saya tidak jadi bunuh diri.”[24]
Kisah dua perempuan hamba yang melarikan diri.
Kisah ini saya dapatkan dari warga desa Z tentang dua perempuan hamba yang melarikan diri dari rumah tuannya. Saya tidak pernah bertemu dua perempuan hamba ini. Kisah mereka saya dapatkan dari penuturan 7 orang laki-laki dan perempuan dari kasta maramba dan ata yang berasal dari desa Z. Dua perempuan hamba ini sejak kecil tinggal dengan sebuah keluarga bangsawan. Mereka telah punya suami dan anak.
Si tuan kerap melakukan pelecehan seksual pada hamba perempuannya ini. Mereka akan dipukul jika menolak untuk disetubuhi oleh tuannya. Mereka lari meninggalkan desanya, meninggalkan anak dan suaminya. Kisah ini diketahui sebagian besar warga desa tidak ada yang berani melaporkan. Mereka hanya bercerita.[25]
Penuturan lainnya dari Tawuru May 20 tahun:
“Ada juga hamba yang punya anak tetapi tidak ada suami. Nanti itu hamba punya anak-anak jadi tau la umma-nya dorang [para bangsawan] sudah. Jadi dorang punya anak buah. Bos tidak marah, malah dorang senang sudah yang penting punya anak biar tidak ada suami. Di kampung sana [menyebutkan nama kampung] ada yang begitu.”[26]
Perempuan Hamba yang “Dipakai” oleh Tuannya
Kisah lainnya saya dapatkan pada tahun 2006. Saya bertemu dengan seorang perempuan Hamba, Yani, sekitar 23 tahun di Kota Waingapu. Dia bercerita bahwa tuannya baru belis [perempuan] hamba sekitar dua minggu lalu. Usianya 13 tahun.
“Bos bilang, saya sudah cape belis dia, saya “pakai” dulu [setubuhi dulu].”
Beberapa hari kemudian, saya mendampingi seorang perempuan jurnalis yang sedang menulis tentang perbudakan di Sumba. Dan sangat kebetulan rumah tuan Yani yang kami datangi. Sambil menunggu jurnalis ini melakukan tugasnya, saya berjumpa dengan para hamba, saya berbincang santai dengan mereka. Seorang hamba sambil senyum menunjuk seorang remaja perempuan.
“Ini dia baru dibelis sama bos. Dia baru di sini. Dia dengan bos dulu,” ujarnya dan disambut tertawa kecil oleh beberapa perempuan hamba lainnya. Perempuan hamba yang baru dibelis ini menunduk saja. Kami pindah ke topik perbincangan lain.[27]
Istilah “pakai” dalam konteks penguasaan tubuh perempuan hamba ini diungkapkan juga oleh Pater Robert Ramone yang juga adalah pastor dan budayawan.
“Misalnya A [laki-laki] menikah dengan B [perempuan], lalu hambanya di B lebih cantik dari istrinya, nah itu dia [A] bisa “pakai” si hamba tadi. Nanti akan melahirkan hamba. Status anak yang lahir tadi tidak sama status anak dari istrinya, ya dia tetap hamba. Ini dilestarikan ya tetap dilestarikan. Meruntuhkan ini sulit karena orang-orang yang kita harapkan menjadi tokoh perubahan masih memuja perbudakan.”[28]
Masih tentang istilah “pakai”, Pendeta Marlin Lomi, Ketua Umum Sinode Gereja Kristen Sumba juga menuturkan hal yang serupa.
“Kalau mau jujur meneliti masih banyak relasi yang kurang baik meskipun sudah Kristen tapi sikap tutur kata dan perilaku terhadap mereka yang dianggap hamba itu aduh memang miris juga. Ya kalau mau lihat jangankan di desa, di lingkungan kota ini yang orang-orang pejabat, nah perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi bukan hanya soal dia marah dia maki dia pukul, tapi yang lebih sadis ini ini dia “pakai” ini hamba. ……..[ Apakah dia setubuhi, dia perkosa?]. Ya dia setubuhi. Hamba dalam ketidakmampuannya apa ya, untuk mengelak atau menolak, ………… ya biasanya orang Sumba Timur bilang itu anak kalawihi. Anak kalawihi itu artinya anak raja [maramba] dengan hamba di rumah. Dia taruh anak. Kadang bukan hanya bapaknya tapi juga anak laki-lakinya, dia taruh anak.”[29] Taruh anak yang dimaksud di sini adalah perempuan hamba disetubuhi hingga hamil dan punya anak. Gambaran yang disampaikan Pendeta Marlin lokasinya di Sumba Timur.
Politik penguasaan tubuh perempuan dalam sistem perbudakan terjadi di berbagai daerah, berbagai negara. Dalam kisah perbudakan Batavia tahun 1619 dituliskan bagaimana transaksi budak baik laki-laki maupun perempuan, perempuan dan laki-laki sebagai suami istri dan jika memiliki anak akan berbeda harga jualnya.[30]
Pater Robert menjelaskan kondisi perbudakan di abad ke-15 yang masih terjadi saat ini di Sumba .
“Perdagangan budak waktu itu [abad ke-15], ya budak laki-laki budak perempuan. Perbudakan itu tidak mengenal gender. [Apakah ada beda harga budak yang laki dan perempuan?]. Tentu saja, laki-laki dianggap tenaga kerja yang kuat jadi harganya lebih mahal dibandingkan budak perempuan, harganya lebih turun. [Kalau budak perempuan untuk apa?]. Ah gampang sekali jawabannya. Ini menyangkut kelangsungan hidup mereka. Perkawinan di antara mereka untuk produksi lagi manusia baru untuk melanjutkan perbudakan. Hal itu ada dalam sirkulasi budak belian di Sumba bagian timur. Pernikahan mereka dengan mereka, tidak berkembang, tidak berdaya dan dikuasai.” [31]
Jika merujuk pada I Ketut Ardhana (2005) di atas tadi, kisah perbudakan di Batavia dan kisah para hamba yang menjadi komoditi jual beli atas nama budaya, atas nama tradisi, apakah praktik ini memang dengan sengaja dilestarikan, terutama untuk menguasai rahim perempuan sebagai pelanjut perbudakan dan tenaga kerja gratis? Setelah 500 tahun, setengah abad, praktik ini masih terjadi di Sumba Timur.
Apakah Tradisi Perlu Dipertahankan?
Praktik perbudakan di Sumba masih berlangsung hingga saat ini dan belum ada upaya yang jelas untuk memutus praktik yang mengatasnamakan budaya ini. Negara belum menyentuh isu ini secara tegas meskipun Indonesia telah memiliki Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia. Negara seperti tidak berdaya dan seolah patuh pada pelanggengan praktik perbudakan.
Jika ditelusuri di Sumba Timur, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, kita dapat menemukan aparat negara dan tokoh publik (antara lain ASN, kepala desa) masih memiliki hamba secara turun temurun. Memang ada upaya aparat negara yang dilakukan atas inisiatif perseorangan, misalnya penuturan seorang polisi di Polres Sumba Timur.
“Pernah ada seorang hamba yang bertengkar dengan tuannya karena hamba ini melarikan diri ke Bali. Waktu hambanya datang ke Sumba, tuannya paksa dia untuk kembali ke rumahnya sebagai hamba. Akhirnya diurus di sini [Kantor Polres Sumba Timur]. Saya tanya si hamba, kau mau ikut kembali dia [tuannya] atau bagaimana? Hambanya bilang tidak mau. Saya bilang ke tuannya, itu sudah dengar sendiri khan, ini urusan hak asasi manusia, dia pilih untuk pergi, jadi pergi sudah. Akhirnya si hamba bebas.”[32]
Klaim bahwa perbudakan adalah warisan Marapu, namun mengapa di Sumba Timur yang saat ini didominasi oleh agama Kristen (Protestan dan Katolik) praktik ini masih lestari? Bagaimana dengan ayat-ayat Kitab Suci tentang kesetaraan di hadapan Allah yang banyak dikutip dalam kotbah di rumah ibadah? Apakah pemuka agama Kristen masih ada yang memiliki hamba?
Pendeta Marlin menuturkan:
“….ada pelayan Tuhan, pendeta yang punya hamba dan tinggal bersama, ya karena dia hamba, makan tidak semeja, bahkan juga tidak mendapat perlakuan-perlakuan yang sewajarnya, dalam memanggil saja harus umbu rambu, saat ini di lingkungan GKS ada. Sampai pada suatu karena sudah tidak nyaman mereka lari meninggalkan tuannya, kalau sudah lari mau dapat di mana lagi?”[33]
Memang sistem ini tidak dapat berakhir dalam sekejap, namun perlu ada upaya afirmatif dari pemerintah daerah misalnya wajib sekolah 12 tahun, tindakan hukum bagi para maramba yang melakukan kekerasan terhadap hambanya dan secara parallel penyadaran kepada penegak hukum. Bukankah tindakan kekerasan terutama terhadap perempuan dan anak adalah delik biasa, bukan delik aduan? Pemerintah juga bisa mengembangkan program-program penguatan kapasitas yang diikuti oleh maramba dan hambanya secara bersama, dan hal inovatif lainnya.
Gereja dapat mengambil langkah konkrit juga. Paling tidak setiap hari Minggu, pemimpin agama akan bertemu umatnya, moment ini dipakai untuk penyadaran, “hukuman” gereja kepada jemaat yang masih mempraktikkan perbudakan misalnya dengan eks-komunikasi, tidak memperbolehkan mengikuti perjamuan kudus atau ekaristi.
Pendeta Marlin baru saja terpilih menjadi Ketua Umum Sinode GKS pada Juni 2022. Dia adalah Ketua Umum perempuan yang pertama sejak GKS lahir pada tahun 1947. Dia menuturkan
“Secara tata gereja maramba yang sudah Kristen, melakukan itu akan dikenai disiplin gerejawi. Siasat, kita bilang. Tidak ikut perjamuan kudus. [Pernah ada?] Kalau yang saya tahu, kalau memang ketahuan kena sudah, tapi ya lebih banyak tutup mulut, kalau ketahuan ya tutup mulut. [Belum ada yang terungkap?] Ya masalahnya kalau stratifikasi sosial seperti ini masalah sensitive, kalau hamba buka ya nyawa taruhannya. Kita gereja kalau tidak pegang bukti sulit untuk kenakan sistem gereja. Selama ini kita tetap melakukan pendampingan, penginjilan di semua jemaat termasuk para maramba. Ke depan ini, kita memang mesti angkat terus, persoalan ini. Mungkin dalam diskusi tematik sebelum Sidang Sinode, kita angkat isu-isu krusial di sekitar kita, persiapan vicariat terutama saat akan ditahbis jadi pendeta, juga bagi para majelis gereja.”[34
Perbudakan tradisional seperti ini sudah lama ditinggalkan oleh negara-negara lain, daerah lain di Indonesia. Jika praktik ini tidak segera diputus, maka Sumba akan tertinggal 100 tahun bahkan lebih.
Apakah kita mau?
Mungkin saja banyak maramba yang punya niat untuk membebaskan hambanya, tetapi belum menemukan cara yang tepat. Kita bisa memberi solusi pada mereka.
Catatan Kaki:
[1] Penulis dan Peneliti dari Sumba
[2] Nama desa dan narasumber disamarkan untuk melindungi narasumber. Lokasi wawancara dan pengamatan di Sumba Timur.
[3] I Ketut Ardhana, Penataan Nusa Tenggara Pada Masa Kolonial 1915-1950, PT Raja Grasindo Persana, 2005, Jakarta
[4] Wawancara 22 Oktober 2022
[5] Wawancara 22 Oktober 2022
[6] https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perbudakan diakses 3 Oktober 2022
[7] https://tirto.id/sejarah-perbudakan-di-indonesia-pengertian-dan-contohnya-di-dunia-gol6?page=all#secondpage
diakses 3 Oktober 2022.
[8] Dalam arti yang lain, kabihu adalah klan (garis patrilineal, merujuk pada garis keturunan ayah). Kaum bangsawan, kaum merdeka dan kaum hamba memiliki kabihu. Kabihu para hamba biasanya mengikuti kabihu para bangsawan yang memiliki mereka.
[9] Ata (Bahasa Kambera) berarti hamba. Tau la umma (Bahasa Kambera) berarti orang dalam rumah atau biasa disebut juga anak dalam rumah, merupakan sebutkan halus untuk ata.
[10] F.D. Wellem, BPK Gunung Mulia, 2002, Injil dan Marapu, Suatu Studi Histori – Teologis tentang Perjumpaan Injil dengan Masyarakat Sumba pada Periode 1876-1990.
[11]https://projectmultatuli.org/tuan-rumah-yang-dipinggirkan-umat-marapu-dulu-didiskriminasi-agamanya-kini-hidupnya-ditekan-proyek-swasembada-gula-jokowi/ diakses 10 September 2022
[12] Martha Hebi, Buku Perempuan (Tidak) Biasa di Sumba Era 1965-1998, RasiBook, 2020, Bandung.
[13] Belis biasanya bermakna mahar, serahan dalam adat perkawinan masyarakat Sumba. Keluarga pihak laki-laki melamar keluarga perempuan dengan hantaran serupa ternak: kerbau atau kuda. Sebaliknya keluarga perempuan akan membalasnya dengan kain sarung tenunan yang indah dan bernilai tinggi.
[14] Nama samaran. Wawancara 20 Oktober 2020 dan 13 November 2021. Lokasi wawancara di Sumba Timur.
[15] Ngara hunga (Bahasa Kambera) artinya nama yang muncul. Dalam tradisi pemberian nama di Sumba Timur paling tidak, ada tiga jenis nama. Ngara pia adalah nama yang diberikan saat lahir, nama yang sebenarnya, nama asli namun tidak disebutkan dan tidak dipakai untuk panggilan sehari-hari. Ngara pa au adalah nama yang digunakan untuk memanggil seseorang dalam kesehariannya. Ngara hunga dalam konteks perbudakan menunjukkan nama yang muncul sebagai identitas seseorang dengan menggunakan nama hambanya, tanda bahwa bahwa dia memiliki hamba dengan nama yang dipakai si bangsawan. Sedangkan nama bangsawan ini tidak disebutkan. Misalnya Rambu nai Lemba (Rambunya Lemba) untuk menyebutkan perempuan bangsawan yang memiliki hamba bernama Lemba. Nama asli perempuan bangsawan misalnya Rambu Konga. Wawancara Triawan Umbu Mehakati, 21 November 2022, Waingapu.
[16] Nama samaran, Wawancara 12 September 2022. Lokasi wawancara di Sumba Timur.
[17] Nama samaran. Wawancara 13 November 2021, Lokasi wawancara di Sumba Timur.
[18] Nama samaran. Dari catatan lapangan, wawancara dan pengamatan 22-24 Juli 2003. Lokasi wawancara di Sumba Timur.
[19] Nama samaran. Dari catatan lapangan, hasil pengamatan. 22-24 Juli 2003. Lokasi wawancara di Sumba Timur.
[20] Nama samaran. Wawancara 13 November 2021. Lokasi wawancara di Sumba Timur.
[21] Nama samaran. Wawancara 20 Oktober 2020 dan 13 November 2021. Lokasi wawancara di Sumba Timur.
[22] Nama samaran, Wawancara 12 September 2022. Lokasi wawancara di Sumba Timur.
[23] Nama samaran. Pengamatan dan wawancara 19 – 22 Juli 2003. Lokasi wawancara d Sumba Timur.
[24] Nama samaran. Wawancara dan diskusi sejak 2019 – 2021. Lokasi wawancara di Sumba Timur.
[25] Pengamatan dan wawancara 2020 – 2022. Lokasi wawancara di Sumba Timur.
[26] Nama samaran. Wawancara 13 November 2021. Lokasi wawancara di Sumba Timur.
[27] Nama samaran. Lokasi wawancara dan pengamatan di Sumba Timur.
[28] Wawancara 22 Oktober 2022.
[29] Wawancara 22 Oktober 2022.
[30] https://bataviadigital.perpusnas.go.id/kisah/?box=detail&id_record=7&npage=1&search_key=&search_val=&status_key=&dpage=1 diakses 15 Oktober 2022.
[31] Wawancara 22 Oktober 2022.
[32] Percakapan dengan anggota polisi di Polres Sumba Timur Februari 2020.
[33] Wawancara 22 Oktober 2022.
[34] Wawancara 22 Oktober 2022

Info Kontak
Jika ada pertanyaan atau kritik silahkan hubungi kami
